Ketika Elite Sudah Berlari, Negara Masih Berjalan
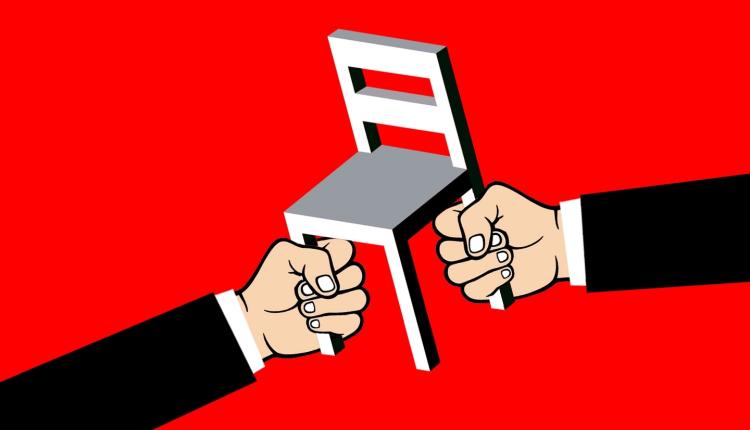
Ilustrasi. (poto/net).
Penulis: Jufri, Pegiat sosial politik dan dakwah Kebangsaan
Satuju.com - Politik bukan sekadar soal siapa menang dan siapa kalah. Ia adalah soal watak. Soal bagaimana kekuasaan dipahami: sebagai amanah atau sebagai milik. Karena itu, ketika elite sudah sibuk memproyeksikan Pilpres 2029 saat pemerintahan baru berjalan setahun lebih sedikit, publik wajar bertanya: apakah mereka sedang bekerja untuk negara, atau sedang bekerja untuk diri dan lingkarannya sendiri?
Pernyataan Ahmad Ali dari PSI yang menyebut Gibran Rakabuming Raka sebagai kandidat paling layak dan siap menjadi lawan Prabowo bukan sekadar ekspresi optimisme. Ia adalah sinyal tentang arah ambisi. Terlalu cepat, terlalu percaya diri, dan terlalu mengabaikan etika waktu.
Di saat bangsa ini masih berkutat dengan bencana, tekanan ekonomi, dan ketidakpastian masa depan generasi muda, elite justru sibuk menyusun papan catur kekuasaan. Seolah-olah urusan rakyat hari ini sudah selesai. Seolah penderitaan sosial bisa ditunda karena elite lebih tergoda membicarakan kursi esok hari.
Lebih dari itu, pernyataan semacam ini berbahaya karena berpotensi menciptakan polarisasi terbuka antara Prabowo dan Gibran. Padahal mereka adalah satu paket kepemimpinan, satu mandat rakyat. Jika sejak awal sudah dipisahkan secara politis, maka yang lahir bukan kerja kolektif, tetapi kecurigaan.
Akan muncul persepsi: ada menteri “Prabowo”, ada menteri “Jokowi–Gibran”. Ada yang fokus bekerja untuk presiden, ada yang diam-diam menata posisi untuk 2029. Kabinet yang seharusnya solid berubah menjadi arena konsolidasi kekuasaan. Dan negara tidak bisa berjalan baik di atas faksi-faksi yang saling menunggu momentum.
Di titik inilah pernyataan Ahmad Ali justru menjadi sinyal kuat agar Prabowo lebih berhati-hati terhadap Gibran. Sesuatu yang seharusnya tidak perlu terjadi, jika saja Gibran dan kelompok Jokowi lebih sabar, lebih menahan diri, dan lebih menghormati etika kekuasaan. Presiden dan wakil presiden seharusnya dibangun di atas rasa saling percaya, bukan di atas kewaspadaan politik satu sama lain.
Dalam konteks ini, kritik PDIP bukan soal Gibran sebagai pribadi semata, tetapi soal mentalitas kekuasaan yang merasa sudah unggul sebelum membuktikan kerja. Terlebih ketika publik juga melihat sikap jumawa di tengah sorotan etik dan hukum, yang semestinya melahirkan kerendahan hati, bukan keberanian memproklamasikan diri sebagai “yang paling pantas”.
Namun ada juga sisi baiknya. Rakyat jadi melihat lebih terang betapa besar ambisi politik keluarga Jokowi dan lingkaran Gibran. Sampai-sampai Gibran sudah disebut sebagai capres, saat pemerintahan baru berjalan sebentar, dan Prabowo masih sibuk mengurai berbagai masalah warisan kekuasaan sebelumnya.
Di titik ini publik berhak bertanya yang sedang diperjuangkan ini keberlanjutan negara, atau keberlanjutan dinasti?
Politik kita terlalu sering tergelincir dari pengabdian menjadi perlombaan gengsi. Dari amanah menjadi proyek ego. Dari kepemimpinan menjadi panggung pencitraan.
Negeri ini tidak kekurangan orang yang ingin jadi presiden.
Negeri ini kekurangan orang yang sungguh-sungguh ingin mengabdi.
Dan sejarah bisa saja kejam kepada mereka yang terlalu cepat memikirkan kursi, ketika rakyat masih menunggu kerja nyata.
Silaturahmi Kolaborasi Sinergi Harmoni

